Kenapa Fenomena Working Wife Begitu Problematik di Negara Ber-Flower?
10:30 AMFirst post di 2020! Postingan pertama tahun ini saya dedikasikan untuk topik hangat yang nggak ada habisnya jadi problematik di negara berflower ini. Working wife hampir selalu jadi momok bagi setiap pasangan. Bahkan jauh-jauh sebelum
menikah, banyak pasangan (including me
and my bf) jungkir-balik mendiskusikan ini.
This is indeed a crucial issue in
marriage life. Dan, ya, ini memang harus didiskusikan
bareng pasangan. Bahkan perdebatan tentang working
wife ini nggak cuma berada di level pasangan saja, tapi sampai level
(calon) mertua. Saya dan Bang Pacar bahkan nggak ada habisnya ngomongin perihal
apakah saya nanti harus bekerja atau tidak setelah menikah. Bahkan kami bisa
sampai level lomba debat SMA tingkat provinsi 😅.
Here’s the cores of our debate:
- Saya sekarang masih berstatus mahasiswa pascasarjana yang belum punya pekerjaan tetap, tapi ingin berkarier.
- Bang Pacar adalah seorang pegawai baru di salah satu BUMN, yang sudah menyetujui poin “BERSEDIA DITEMPATKAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA”.
- We both agree that long-distance marriage is not fit for us, because physical touch and quality time are our love language, that’s impossible to obtain if we’re separated by distance.
But before I continue, a little
disclaimer: I
don’t meant to accuse or generalise men or family at all. Saya sendiri
belum menikah dan mungkin opini saya terdengar naif. Saya pun bahkan belum tau
karier saya ke depannya (iya, iya. nggak
punya perencanaan banget anaknya emang).
“Udah, kamu
nggak usah kerja. Di rumah aja tungguin aku. Biar aku yang cari uang buat
keluarga kita.”
“Cari duit biar
urusanku, kamu fokus aja ngurusin anak-anak.”
Women, what do you think, when a man
(that is your husband by a chance) told you that?
Beberapa perempuan mungkin melting dan menganggap kalimat-kalimat di
atas romantis. Bahkan si suami sukses membentuk self-image sebagai “lelaki
bertanggung jawab” di mata istri.
Same energy with para orang tua dan (calon) mertua yang bilang:
"Nanti mending kerja jadi X aja, biar punya banyak waktu di rumah."
"Mending kalau udah punya anak berhenti kerja. Jangan kaya si X, lihat tuh gara-gara istrinya sibuk cari duit anaknya jadi nggak keurus!" (julid mode: activated)
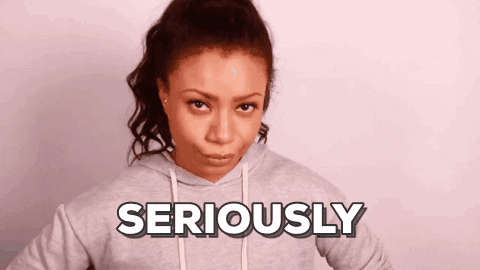 |
| Source: Giphy |
Kalimat-kalimat diatas justru terasa limiting,
intimidating dan underestimating
bagi sebagian perempuan. Sebab jujur kalimat-kalimat itu tidak sama sekali
terdengar seperti sedang “memuliakan perempuan” bagi saya. Malahan terkesan seperti mengkotak-kotakkan peran gender diantara laki-laki dan perempuan.
Suami adalah tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab atas
keluarga. There’s no doubt about it. Our
religion teachs us. But thoughts like
women are always seen as complementary in the context of livelihood is not the
part of religious teachings. It’s socially constructed. Hal ini pasti nggak bakal jauh-jauh dari peran gender
yang sudah kepalang tanggung jadi DNA dalam budaya patriarki.
Peran gender seolah-olah mendikte apa yang harus dilakukan laki-laki dan
perempuan. Laki-laki di kantor, perempuan urus pekerjaan domestik. Bahkan
sedari kecil anak laki-laki & anak perempuan sudah diberi distinctions. Mulai dari pilihan warna
(laki-laki biru, perempuan pink) hingga pilihan mainan (laki-laki mobil-mobilan
atau pistol-pistolan, perempuan boneka bayi atau mainan masak-masakan) yang
akhirnya berujung jadi pemahaman bersama di lingkungan sosial tentang peran
istri dan suami. And when women try to
take what society believes as “man’s role”, that’s become problematic.
Karena terlalu problematiknya, bahkan banyak cara melimitasi peran
perempuan di dunia kerja: perempuan dianggap tidak lebih kompeten dibanding
laki-laki, diberi upah yang tidak setara dengan laki-laki, bahkan dianggap
sebagai penyebab tingginya angka pengangguran.
Wait, WHAT?
Ini beneran, lho. Suatu hari
saya mendapati seorang yang saya kenal me-repost
postingan dari akun “so-called” dakwah di Instagram.
Kira-kira begini bunyi postingannya:
Gemes yah, bacanya? Saya juga. Akun-akun kayak
begini, nih yang bikin stigma negatif
terhadap perempuan bekerja laku keras di negara +62.
First, logika seperti ini jelas saja menyimpang. Jaka Sembung makan gulali, nggak nyambung kaliiiii (okay, pantun jayus
mode activated). Second, nggak ada fakta dan data sama sekali
yang melandasi statement ini, 100%
statement diramu dengan emotional-appeal
belaka. Third, yang banyak komentar
memang kaum adam, gaes, hahaha. Taruhan deh, yang bikin ini post
adalah laki-laki.
Talking about data. Menurut data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari BPS, masih
ada ketimpangan
partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2018 tercatat TPAK laki-laki sebesar 82,69 persen,
sedangkan TPAK perempuan hanya 51,88 persen. Jadi sebenarnya masih ada gap yang cukup besar dalam keterlibatan
ekonomi perempuan. Untuk masalah pengangguran, para expert di bidang talent development
nggak pernah nge-claim kalau penyebab banyaknya pengangguran karena wanita yang
bekerja, tapi karena nggak
seimbangnya supply & demand
antara kebutuhan industri & kompetensi SDM yang tersedia.
Lalu, apa lagi yang bikin fenomena working
wife begitu problematik?
Toxic Masculinity
Perempuan yang bekerja karena gengsi? Banyak. Tapi, perempuan yang tidak
bisa bekerja karena dianggap menjatuhkan gengsi pasangan juga banyak. Salah
seorang teman pernah ditanya tentang bagaimana jadi istri yang baik. Coba tebak
jawabannya. Dia menjawab “dengan menjadi
terlihat lemah di depan suami, agar suami merasa kuat dan menjadi pelindung”.
Duh, maaf teman, tapi kita tak sependapat. If he’s really a strong man, then we don’t need to pretend like we’re
the weak one. Anggapan bahwa “kodrat” perempuan adalah lebih lemah dari
laki-laki adalah bentuk toxic masculinity.
Itu sebabnya ketika perempuan lebih unggul dalam satu hal dibanding laki-laki,
dianggap merusak tatanan sosial yang ada. Seorang laki-laki nggak perlu merasa minder hanya karena pasangannya lebih baik dalam satu atau dua hal.
Lagi pula setiap orang, termasuk perempuan, diberkahi dengan kelebihan
masing-masing, kan?
Vibes yang sama saat si suami melarang istri bekerja untuk menunjukkan rasa
tanggung jawabnya. Hey, that’s not how
you show it. Masih banyak cara lain untuk menunjukkan responsibility.
In the end of the day, jika kedua belah pihak sama-sama sepakat agar istri tak bekerja, then it’s not a burden. Yang jadi
masalah ketika ada paksaan yang didasari alasan-alasan toxic masculinity seperti di atas. Lalu, beruntunglah buat mereka
yang sudah diberkati kekayaan yang mengalir sampai jauh kayak pipa Ruc*ka. Tapi bagaimana dengan mereka yang kondisi
ekonominya pas-pasan? Peran istri yang bekerja akan sangat membantu keluarga untuk
keluar dari financial insecurity.
“Yah, kalau istri mau bekerja, kan bisa yang nggak keluar rumah. Bikin
olshop aja gitu.”
Ya, ngomong mah gampang,
Bambang! Sayangnya nggak semua
perempuan juga diberkahi dengan kesempatan ekonomi yang sama. Some women are gifted by capital, but some
others are not. Nggak semua
perempuan juga kali, yang punya bakat berdagang, kecuali dia uni-uni Padang
atau cici-cici Glodok (yhaaa stereotiping
deh, lol). Lagi-lagi, setiap orang punya jalan dan pintu rejeki
masing-masing, bukan begitu?
Women Just Seen As A Passive Entity
Last but not least, setiap individu punya pemaknaan yang berbeda akan konsep karier. Perlu
diketahui, karier bukan melulu soal perekonomian, bukan cuma tentang cuan. Sebagian orang memandang karier
sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan personal
lainnya.
Pernah dengar Maslow’s
Hierarchy of Needs? Sejatinya ini adalah teori dalam ilmu
psikologi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Menurut teori ini, manusia tuh punya banyak tingkatan kebutuhan.
Mulai dari yang paling dasar berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, rasa aman,
rasa dicintai dan rasa memiliki, self
esteem, hingga yang paling tinggi, kebutuhan aktualisasi diri. Manusia akan
cenderung untuk memenuhi segala tingkatan kebutuhannya. Jika salah satunya
tidak terpenuhi, well, welcome
insecurity.
Kebutuhan fisiologis dan rasa aman mungkin saja pemenuhannya bisa diperoleh dari orang lain. Sementara itu, karier dalam hal ini bisa berada di posisi self-esteem needs atau self-actualization needs, dimana kedua kebutuhan ini belum teentu, atau bahkan nggak mungkin untuk dipenuhi oleh orang lain, sekalipun suami sendiri!
Kebutuhan fisiologis dan rasa aman mungkin saja pemenuhannya bisa diperoleh dari orang lain. Sementara itu, karier dalam hal ini bisa berada di posisi self-esteem needs atau self-actualization needs, dimana kedua kebutuhan ini belum teentu, atau bahkan nggak mungkin untuk dipenuhi oleh orang lain, sekalipun suami sendiri!
So, jangan menyederhanakan makna karier hanya sebagai sarana mencari
nafkah. Lebih dari itu, karier juga dianggap sebagai sarana pemenuhan kelima
tingkatan kebutuhan ini. Apakah suami bisa sendirinya otomatis memenuhi seluruh
tingkatan kebutuhan istrinya? Unless thay
had super powers, then they can’t.
Stop seeing your wife as an object that has to obey everything you told her as a “leader”. Look at her as she is a mere human being. Perempuan juga punya kebutuhan, keinginan, dan cita-cita. Respect them as you want to be respected as well.
Well, ini sih opini saya, sebagai seorang anak baru gede (yang hampir seperempat abad) dan dianggap “tau apa sih tentang pernikahan?” orang
masih single. But hey, why don’t we try to open our eyes and mind?


![About [span]me[/span]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjGuUXCVK845fdFou9APDGtLXI_KTAuzNsWttExCgTzAXVq0qVnNj4fHlMSuMJDCS5aKcYfj23iIZJPCIHNAeBWMEgMMPC_NF18d-NngPu0bzI9-T1eeTTco29s3JlxmEUkx33yQU2/s2048/IMG_7552.JPG)

0 Comments